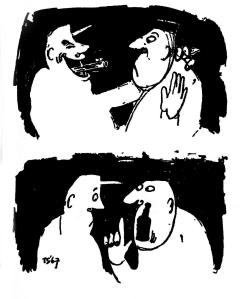DI SAMPING semua ini kita catat komando-komando Aidit –pidato-pidato 11 Mei dan 23 Mei di depan Hari Ulang Tahun PKI ke-45– buat mengganyang semua kapitalis birokrat, semua kaum anti Manipol, semua kaum anti Nasakom, kaum anti Komunis, kaum Trotzkys, kaum lima setan, termasuk kaum kapbir (kapitalis birokrat) dan tujuh setan desa.
Tanggal 25 Juli Bung Karno mengomandokan supaya semua “PNI gadungan” ditendang dari PNI. Ini sesungguhnya adalah komando buat semua organisasi non komunis dan anti komunis untuk memecah belah diri mereka sendiri dengan saling mencurigai, saling menuduh, saling memfitnah, dan saling menendang. Tahun 1964 juga sudah ada komando-komando seperti ini.

Inilah politik divide et impera Soekarno buat menjamin kokohnya kekuasaan PKI. Bung Karno mempraktekkan Marxisme-Leninisme-Maoisme. Sekarang tinggal meledakkan Revolusi Sosial-nya. Tapi untuk ini diperlukan senjata. Di samping itu ABRI yang anti komunis harus dihancurkan dulu. Sukses Revolusi Sosial hanya terjamin kalau diktum Mao Zedongdilaksanakan: “Political power grows out of the barrel of a gun” (Mao Zedong, On Contradiction).
Menghancurkan ABRI dan Gerakan 30 September
Karena ABRI adalah anti-komunis, maka ABRI harus dihancurkan, demi meratakan jalan buat perebutan kekuasaan oleh PKI.
Caranya ada empat.
Pertama, ABRI harus disusupi dengan komunisme, sehingga pecah menjadi ABRI-komunis dan ABRI anti komunis. Keduanya gampang diadu. Ternyata infiltrasi ini berhasil.
Kedua, ABRI harus di-Nasakom-kan. Ini tidak berhasil sebab ditentang Abdul Harris Nasution dan Ahmad Yani.
Ketiga, ABRI harus disuruh berperang melawan Inggeris supaya kekuatan ABRI bisa dipatahkan atau dihancurkan sama sekali. Untuk itu diperlukan perang terbuka di mana Inggeris melakukan invasi terbuka ke dalam wilayah Indonesia. Untuk memprovokasikan agresi Inggeris ini maka pasukan tertentu diterjunkan ke Semenanjung Malaya. Tapi Inggeris tetap tidak bereaksi. Mereka tetap berdiam diri saja di Singapura dan paling-paling hanya menjaga perbatasan. Pihak sana rupanya mengerti bahwa perang terbuka berarti peng-komunis-an Indonesia secara total. Dengan demikian, usaha eksploitasi politik konfrontasi ternyata gagal.
Keempat, karena gagalnya politik konfrontasi ini, maka Bung Karno mau membentuk “ABRI tandingan” yang namanya “Angkatan Kelima”. Bung Karno menyodorkan gagasan kepada ABRI. Gagasan ini dikatakan datang dari PM RRC Chou En-lai. Segera PKI dan semua organisasi massanya menuntut “minta dipersenjatai”. PNI dan ‘Suluh Indonesia’ juga memberi sokongan penuh. Kata Ali Sastroamidjojo kepada ‘Antara’ (23 Juli 1965), “Integrasi antara rakyat dan ABRI harus dilaksanakan dalam bentuk Angkatan Kelima”. Sejak bulan Mei Harian ‘Suluh Indonesia’ juga mempropagandakan idea Angkatan Kelima ini. Dan Bung Karno meng’amanat’i ABRI dengan mengatakan “bahaya kuning dari Utara itu tidak ada”, untuk menepis kekuatiran yang sebelumnya disampaikan para pimpinan Angkatan Darat.
Angkatan Kelima ini gagal dilaksanakan, karena sikap keras dan tegas Nasution dan Ahmad Yani. Semua kegagalan merobek ABRI ini membuat avontur Gestapu (‘Gerakan September Tiga Puluh’) sebenarnya menjadi riskan. Peluangnya hanya setengah-setengah. Tetapi situasi revolusi diyakini oleh sebagian tokohnya sudah ‘masak’. Dianggap keadaan sudah “hamil tua”. Gerakan mesti dipaksakan.
Beberapa hal jelas merupakan persiapan Gerakan 30 September.
Anwar Sanusi berkata di bulan September bahwa “Ibu Pertiwi sudah hamil tua”. Tanggal 9 September Aidit berpidato: Sang bayi pasti lahir. Adalah kebiasaan Lenin untuk mengumpamakan “situasi revolusioner” sebagai “keadaan hamil”. Dus, “hamil tua” berarti “siap untuk segera dilahirkan”. Aidit mengatakan “kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi pasti lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar”.
Dalam sambutannya pada hari lahir ke 34 Partindo, yang dibacakan oleh salah satu menterinya Oei Tjoe Tat, Bung Karno menutup pidatonya dengan kata-kata, “Pergunakanlah Harlah ke-34 Partindo ini untuk meningkatkan implementasi komando saya untuk menyelesaikan Revolusi Nasional Demokratis Indonesia ini serta mengadakan persiapan-persiapan untuk memasuki periode Sosialisme Indonesia”. Jadi dalam keadaan negara yang bobrok waktu ini, Bung Karno memberi komando supaya bersiap-siap untuk memasuki Sosialisme Indonesia. Padahal “syarat-syarat kesejahteraan sosial dan hamil dengan kesejahteraan”, seperti yang pernah dikatakannya sendiri, sama sekali tidak ada. Tidak bisa tidak komando ini harus kita artikan sebagai komando untuk bersiap-siap menjalankan satu aksi, yakni Gestapu.
Pada tanggal 26 September 1965, hanya lima hari sebelum Gerakan 30 September, Presiden Soekarno berkata di depan lulusan-lulusan Institut Pertanian Bogor dalam upacara di Istana Bogor, “Tahap pertama dari Revolusi Indonesia, yaitu tahap Nasional Demokratis, sudah hampir selesai. Kita sekarang sudah diambang pintunya tahap kedua dari Revolusi Indonesia, yaitu pelaksanaan sosialisme”.
Sudah terang yang ada diambang pintu saat itu adalah “Revolusi Sosial”nya Gerakan 30 September. Selebihnya hanyalah ada kemelaratan, inflasi, dan ketidakadilan sosial, dan menghebatnya segala macam kebobrokan. Maka kita harus mengambil kesimpulan bahwa Bung Karno mengetahui benar tentang bakal adanya aksi Gerakan 30 September. Karena itu Bung Karno adalah pelaku Gerakan 30 September. Bung Karno adalah dalang utama Gerakan 30 September, atau salah seorang dalangnya.
Berhasil atau tidak ?
“Rezim Soekarno gagal”, kata rakyat sekarang. Bung Karno menjawab, “Aku berhasil”.
Yang berbeda di sini adalah view point. Rakyat memakai Pancasila sebagai ukuran, sedang Bung Karno memakai Marxisme sebagai ukuran. Ternyata Pancasila dan Marxisme tidak klop, malahan bertentangan dalam penilaian.
Dari sudut pelaksanaan Marxisme-Leninisme, Bung Karno memang berhasil. Bung Karno berhasil membangun Kediktatoran Demokratis Rakyat. Bung Karno berhasil mematangkan situasi revolusioner. Bung Karno berhasil memecah belah dan menyapu bersih kekuatan-kekuatan dan tokoh-tokoh anti komunis. Bung Karno berhasil mendudukkan PKI ke posisi berkuasa. Aksi Gerakan 30 September (Gestapu) adalah tugas mulia sebagai Marxis-Leninis yang sejati-konsekuen-revolusioner.
Bung Karno bukanlah seorang Pancasilais. Pancasila adalah hogere optrekking dari Marxisme. Artinya, Pancasila adalah lebih tinggi dari Marxisme. Seharusnya Bung Karno berkata, “Aku adalah Pancasilais yang sudah mengatasi Marxisme”. Tapi Bung Karno tidak mengatakan itu. Belakangan, Bung Karno terus menerus berkata, “Aku adalah Marxis”.
Sungguh celaka.
*Marion Mueng Yong adalah nama yang digunakan Dr Soedjoko MA setiap kali menulis. Soedjoko seorang cendekiawan terkemuka, pengajar ITB yang menjadi aktivis. Memiliki gaya menulis yang memikat dan tajam. Tulisan ini berjudul asli “Siapa Dalang Gestapu?” dimuat serial selama 3 minggu di Mingguan Mahasiswa Indonesia, Bandung, akhir September dan awal Oktober 1966. Kemudian menjadi salah satu artikel koleksi dalam buku “Simtom Politik 1965” yang terbit 2007. Soedjoko termasuk salah satu yang meyakini keterlibatan penuh Soekarno dalam Peristiwa 30 September 1965. Meninggal dunia tahun 2006.
(socio-politica.com)