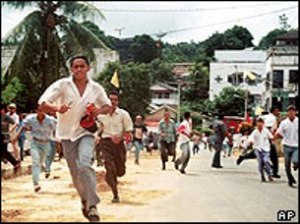SIAPAKAH Bung Karno? Bung Karno –atau Ir Soekarno, yang nama lengkapnya adalah Raden Koesno Sosro Soekarno– lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Memperoleh gelar ingenieur di Bandung tahun 1925. Menurut tulisan Aldy Anwar, “ia adalah seorang yang cerdas, berbakat luar biasa dan berambisi besar.”
Semasa remajanya Raden Koesno Sosro Soekarno telah jatuh cinta pada teman sekolahnya di HBS, seorang anak Belanda bernama Mien Hessels. Setelah berkasih-kasihan beberapa waktu lamanya, Raden Koesno Sosro Soekarno memberanikan dirinya untuk melamar Mien Hessels kepada ‘Meneer’ Hessels. Tetapi oleh Hessels pinangan ‘inlander R. Koesno Sosro Soekarno yang tak tahu diri itu’ ditolak mentah-mentah dengan caci maki, penghinaan dan pengusiran dari rumahnya.

Peristiwa itu mungkin menimbulkan semacam dendam dalam diri Soekarno kepada Hessels pribadi maupun kepada orang-orang Belanda pada umumnya. “Di bawah pengaruh lingkungan pergaulan di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tempat ia tinggal selama bersekolah di HBS”, dan bertemu dengan tokoh-tokoh politik pemimpin pergerakan dari berbagai aliran, “ia mendapat saluran dalam bentuk sikap anti kolonialisme dan imperialisme Belanda.”
Sebagai student pada Technische Hooge School yang mengalami berbagai diskriminasi dan penghinaan oleh orang-orang Belanda, bertambah kuat tekadnya untuk melawan kekuasaan orang-orang Belanda dan mencari kekuatan sendiri. Menurut Aldy, kemahiran Soekarno untuk mempersuasi orang, ‘akting’ dan berpidato, ternyata berguna baginya dalam klub-klub debat, dan kemudian dalam Bandungsche Studie Club. Kepandaiannya menggunakan kata-kata menyebabkan ia ditarik untuk membantu pers pergerakan seperti “Fikiran Rakjat”. Sasaran tulisan-tulisan dan pidato-pidato agitasinya selalu Belanda dan apa-apa yang diciptakan dan diakibatkan oleh Belanda di Indonesia. “Demikianlah, dengan kepopuleran yang diperolehnya itu Raden Sosro Soekarno atau Ir Soekarno, memulai karir politiknya sebagai pemimpin, yang dalam jangka waktu 40 tahun berhasil membawanya sampai ke puncak kekuasaan dan kejayaan pribadinya.”
Tatkala sesuai keputusan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda tahun 1926, tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang aktif dalam Bandungsche Studie Club memutuskan untuk mendirikan suatu partai yang bercorak nasional, maka Ir Soekarno yang ditonjolkan sebagai ketuanya. Dengan pidato-pidato Soekarno yang menarik massa, PNI dapat menjadi besar. Kepopuleran Ir Soekarno menanjak terus, lebih-lebih setelah ia ditangkap dan dipenjarakan di Banceuy dan kemudian di Sukamiskin.
Sewaktu mahasiswa Mohammad Hatta selaku ketua Perhimpunan Indonesia pada tanggal 9 Maret 1928 dihadapkan Rechtbank di Den Haag, ia mengucapkan pembelaannya yang terkenal, “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka). Di situ ia menguraikan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia serta perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dilakukan Perhimpunan Indonesia. Dalam pada itu, saat Ir Soekarno dihadapkan ke Landraad di tahun 1930, ia mengajukan pembelaan yang hampir serupa bagi PNI, “Indonesia Klaagt Aan” (Indonesia Menggugat). Pembelaan itu menambah kepopulerannya di kalangan pergerakan dan kalangan rakyat banyak.
Selama Ir Soekarno dalam pembuangan di Flores dan Bengkulu, usaha-usaha Dr Tjipto Mangunkusumo, A. Hassan dari Persatuan Islam di Bandung, dan lain-lain dalam pers pergerakan, dapat memelihara kepopuleran Ir Soekarno. Maka tatkala Drs Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir pada permulaan pendudukan Jepang, memutuskan untuk membagi tugas antara memimpin kerjasama dengan Jepang dan memimpin gerakan bawah tanah melawan Jepang, Hatta mengajukan Soekarno yang dianggap pandai ‘bersandiwara’ untuk memimpin kerjasama dengan Jepang.
Semenjak itulah Ir Soekarno dan Drs Mohamamad Hatta dengan dukungan pemimpin-pemimpin lainnya, praktis memegang pimpinan nasional pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh itu mulai terkenal sebagai Bung Karno dan Bung Hatta, serta dipandang sebagai lambang persatuan bangsa dan lambang perjuangan kemerdekaan bangsa. Sehingga wajar dan dianggap dengan sendirinya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus ditandatangani dan diumumkan oleh Soekarno-Hatta. Dan, bahwa sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hanya dipilih Bung Karno dan Bung Hatta. Kepemimpinan Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai pimpinan bangsa, negara dan revolusi adalah suatu kenyataan yang berangsur-angsur juga menjadi mitos.
Tetapi setelah tahun 1950 Bung Karno semakin lebih bersikap sebagai politikus daripada sebagai negarawan. Menjadi pemimpin golongan dan bukan pemimpin bangsa seluruhnya. Semakin melibatkan dirinya dalam percaturan politik dan pertarungan kekuatan, bahkan menjalankan politik devide et impera dan balance of power. Maka, semakin retaklah Dwitunggal Soekarno-Hatta pada tahun 1956. Semakin leluasalah Bung Karno menjalankan politik devide et impera dan balance of power, sementara kepemimpinannya sebagai Bapak Rakyat dan Kepala Negara semakin merosot. Kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan UUDS 1950, dan kemudian UUD 1945, semakin besar dan semakin banyak diperbuatnya.
“Bung Karno pemimpin rakyat semakin terasing dari rakyat, bertahta dalam istana-istana dengan dikelilingi para pemaisuri, dayang dan hulubalang dan tentara istana, bermewah-mewah dan berpelesir di atas penderitaan rakyat yang semakin sengsara. Bung Karno kesayangan rakyat telah meninggalkan dan melupakan rakyatnya. Bung Karno yang dikenal rakyat dahulu, telah tinggal bayangannya saja, tinggal mitosnya saja. Bung Karno yang dahulu, sudah tak ada lagi.” Demikian Aldy Anwar menulis.
SETENGAH tahun kemudian, Maret 1967, masa kekuasaan Presiden Soekarno berakhir. Meski para pendukung Soekarno melakukan tiarap politik panjang setelah itu, untuk sebagian pemitosan Soekarno tak pernah betul-betul berakhir. Tampilnya Megawati Soekarnoputeri sekitar 25 tahun kemudian dengan PDIP, mencuatkan kembali nama Soekarno sebagai simbol keberhasilan dan contoh kharisma suatu model kepemimpinan. Hal yang sama terjadi pada Soeharto setelah 1998. Kini, saat kepemimpinan negara dianggap lemah, nostalgia tentang kejayaan kedua pemimpin itu kembali hidup. Lalu, banyak yang menoleh lagi kepada jalan pikiran, model kepemimpinan, ataupun cara memimpin bangsa dan negara ala Soekarno maupun Soeharto.
Kenapa tidak? Kedua tokoh itu memang sama-sama memiliki keistimewaan, kegemilangan dan keberhasilan. Pantas untuk dicontoh dalam konteks kontinuitas keberhasilan bernegara. Tetapi jangan lupa, sejarah juga mencatat bahwa keduanya pun memiliki banyak kekeliruan dan ketidakberhasilan yang hampir saja menenggelamkan bangsa dan negara ini. Maka bila ingin menarik hikmah dan berkah dari sejarah, mari kita belajar dari pengalaman mereka. Belajar dari keberhasilan mereka, sambil juga belajar titik-titik kegagalan mereka. Cara mereka membawa keberhasilan perlu ditiru, sebagaimana kegagalan mereka dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi. Namun sayang, tak belajar dari sejarah, banyak pemimpin masa kini yang kembali mengulang sejarah: Semakin lebih bersikap sebagai politisi daripada sebagai negarawan. Lebih cenderung menjadi pemimpin golongan dalam konteks kepentingan partainya daripada menjadi pemimpin bangsa seluruhnya.
(socio-politica.com)